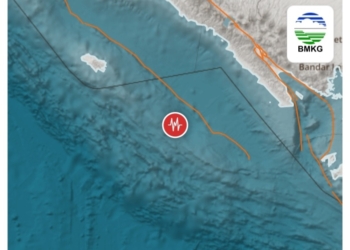BENCANA banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah akumulasi dari kerusakan lingkungan yang berlangsung lama. Mulai dari hutan yang ditebang, daerah resapan yang hilang, dan ekspansi perkebunan sawit yang mengubah lanskap hidup masyarakat. Ketika hujan datang, alam tidak lagi mampu menahan air. Yang tersisa hanyalah lumpur, arus deras, dan rumah-rumah yang tak sempat diselamatkan.
Namun di tengah kondisi yang disebut warga sangat parah, pemerintah tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional. Secara administratif mungkin ada alasannya, tetapi dari sisi komunikasi publik, keputusan ini membawa dampak besar. Status bencana bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal pesan yang disampaikan negara kepada rakyatnya.
Ketika bencana tidak disebut sebagai bencana nasional, masyarakat menangkap pesan bahwa penderitaan mereka dianggap masih dalam batas “biasa”. Padahal, di lapangan, banyak wilayah masih terendam, akses terputus, dan warga hidup di pengungsian tanpa kepastian. Di sinilah jarak antara bahasa pemerintah dan kenyataan warga mulai terasa.
Di media sosial, warga Aceh justru lebih dulu menunjukkan betapa seriusnya kondisi ini. Video rumah hanyut, kebun terendam, dan jalan desa tertutup longsor tersebar luas dan menjadi perhatian publik nasional. Sayangnya, narasi resmi pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dilihat masyarakat melalui unggahan tersebut. Akibatnya, publik bingung, jika kondisinya separah ini, mengapa tidak disebut sebagai bencana nasional?
Perspektif Ilmu Komunikasi
Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, status bencana bukan sekadar istilah administratif. Ia adalah pesan simbolik yang sangat kuat. Ketika pemerintah tidak menyebut sebuah tragedi sebagai bencana nasional, pesan yang sampai ke publik terutama kepada korban adalah bahwa penderitaan mereka dianggap “masih bisa ditangani pada taraf biasa”. Padahal, di lapangan, banyak wilayah masih terendam, longsor masih mengancam, dan warga hidup dalam ketidakpastian.
Komunikasi krisis menuntut kepekaan terhadap realitas sosial dan psikologis korban, bukan hanya kalkulasi prosedural. Saat negara mengecilkan skala bencana dalam narasi resminya, empati publik ikut mengecil. Perhatian nasional pun cepat berpindah. Yang tertinggal adalah warga yang masih membersihkan lumpur, kehilangan mata pencaharian, dan menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
Ironisnya, di era media sosial, warga Sumatera justru lebih dulu memperlihatkan skala bencana melalui video dan kesaksian langsung. Air setinggi dada, longsor yang menutup akses desa, kebun sawit yang menggantikan hutan, dan sungai yang meluap tanpa kendali. Konten-konten ini viral. Publik melihat. Namun narasi resmi negara tidak pernah benar-benar menyamai urgensi visual tersebut.
Dari sudut pandang komunikasi lingkungan, kondisi ini sangat problematik. Pemerintah cenderung memisahkan bencana dari penyebab strukturalnya. Penebangan hutan dan ekspansi sawit jarang disebut secara tegas dalam komunikasi resmi sebagai salah satu penyebab. Banjir seolah hanya disebabkan hujan ekstrem, bukan akibat keputusan pembangunan jangka panjang. Akibatnya, pesan yang diterima publik menjadi dangkal dan tidak edukatif.
Perlu Tanggungjawab
Komunikasi publik yang baik seharusnya tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Ketika penyebab struktural tidak dikomunikasikan, negara kehilangan kesempatan membangun kesadaran ekologis dan kepercayaan publik. Lebih buruk lagi, masyarakat terdampak merasa realitas hidup mereka disederhanakan dalam bahasa birokrasi.
Tidak ditetapkannya bencana ini sebagai bencana nasional juga berdampak pada komunikasi bantuan. Tidak ada satu suara nasional yang konsisten. Tidak ada komunikasi terpadu yang menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya. Dalam teori komunikasi krisis, ketiadaan pesan tunggal yang kuat adalah bentuk kegagalan komunikasi.
Saya melihat persoalan ini bukan hanya soal bantuan, kebijakan, atau anggaran, tetapi soal cara negara hadir lewat kata-kata dan sikapnya. Bahasa yang terlalu teknis dan kaku membuat jarak dengan warga yang sedang berduka. Dalam kondisi seperti ini, korban merasa tak didengar. Ketika penderitaan tidak diberi nama yang setimpal, rasa keadilan pun memudar. Masyarakat tidak hanya butuh bantuan fisik, tetapi juga pengakuan bahwa penderitaan mereka benar-benar dipahami.
Sumatera bukanlah wilayah baru dalam menghadapi bencana. Justru karena itu, negara seharusnya belajar bahwa pengakuan simbolik, melalui penetapan status, bahasa empatik, dan narasi yang jujur adalah bagian penting dari pemulihan. Mengakui bahwa ini adalah bencana nasional bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keberpihakan moral.
Bencana ini sudah sangat parah. Bukan hanya karena air dan longsor, tetapi karena pesan yang sampai ke publik terasa mengecilkan kenyataan. Dalam komunikasi, apa yang tidak diucapkan sering kali lebih menyakitkan daripada apa yang diucapkan.
Jika negara ingin memulihkan, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya tanggul dan jalan, tetapi juga cara berbicara kepada rakyatnya. Karena dalam situasi krisis, komunikasi yang jujur dan empatik adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata. (*)
Shofura Nur Adilah
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung